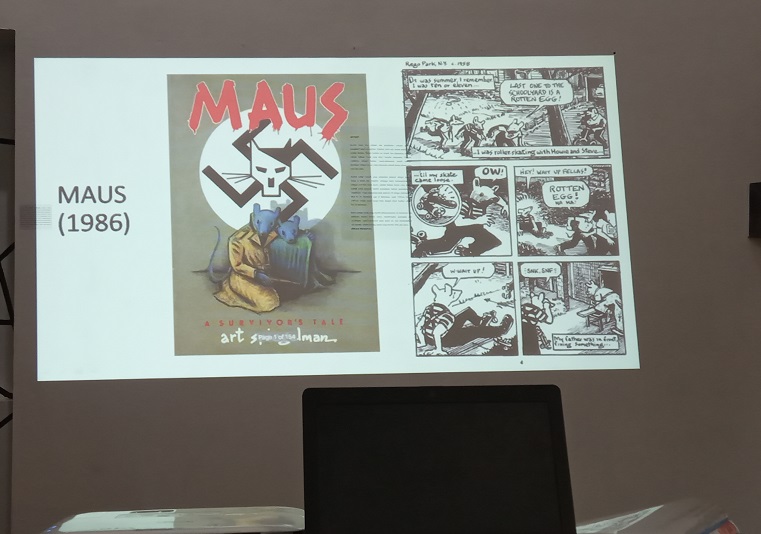Kesombongan sastrawan dalam berkarya
Penari, penyanyi, pemusik, pemain teater memerlukan latihan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan; hanya untuk pentas selama dua jam. Mereka tahu diri, bahwa kreativitas tidak otomatis turun dari langit, tapi perlu diupayakan dengan kerja keras.
Pelukis dan pematung pun kurang-lebih sama. Untuk membuat lukisan atau patung besar; mereka membuat model dalam ukuran kecil. Mereka membuat beberapa model, dipilih, diubah, digabung-gabung, baru kemudian ditentukan pilihan akhir. Dalam memperbesar lukisan dan patung, seniman lukis dan patung dibantu pembuat kanvas, pengecor logam, dan teknisi lainnya. Mereka tidak malu dibantu teknisi. Lain halnya dengan sastrawan. Terlebih mereka yang baru belajar menjadi sastrawan.
Mereka menganggap ilham itu mirip dengan Wahyu Allah yang melesat dari langit, lalu jatuh ke pangkuannya. Setelah mendapat ilham, sastrawan akan secepatnya menulis. Begitu selesai segera ia kirimkan ke redaktur budaya media massa, dengan harapan karya itu segera dipublikasikan. Ketika redaktur budaya menolak karya tersebut, si sastrawan marah. Redaktur budaya dianggapnya bodoh, karena tak bersedia memublikasikan karyanya. Padahal, ditolak atau diterimanya sebuah tulisan di media massa, merupakan hal biasa.
Persiapan dan latihan, tampaknya merupakan barang tabu bagi sastrawan. Bahkan sering seorang calon sastrawan bilang seperti ini, “Yang penting saya nulis, enggak tahu hasilnya puisi, cerpen atau apa.” Padahal sastrawan sama saja dengan perancang busana atau meubel. Mereka sejak awal sudah harus tahu mau bikin baju, celana, meja, kursi, atau lemari? Kan lucu kalau ada perancang busana bilang, “Yang penting saya mencoret-coret kertas, enggak tahu hasilnya jadi baju atau celana.” Lho, maunya bikin baju atau celana?
Tetralogi Bumi Manusia
Mencipta karya sastra, memerlukan pernak-pernik kerja yang remeh-temeh, tak menarik, tapi tetap wajib dilakukan sebagai persiapan. Membaca pustaka, survei lapangan, wawancara dengan narasumber, ngobrol dengan masyarakat biasa; ini merupakan langkah awal. Lho kok sama dengan peneliti, sama dengan wartawan? Ya memang. Karya sastra meskipun berupa fiksi absurd sekali pun, tetap memerlukan data dan fakta. Setelah itu baru membuat kerangka tulisan, lalu kerangka itu diisi dengan otot, daging, darah, dan roh atau jiwa.
Berapa kalikah penari, pemain musik atau penyanyi latihan sebuah tarian, musik atau lagu sampai siap untuk tampil di depan publik? Bisa puluhan kali bukan? Sastrawan pun idealnya menulis sebuah tema (judul) cerita pendek, berkali-kali, sampai bisa menemukan versi yang menurutnya paling kuat. Bagaimana mau menghasilkan cerita pendek bagus kalau setelah menemukan ilham langsung menulis, kadang tanpa dibaca ulang, langsung dikirim ke redaktur media? Inilah salah satu ketololan, sekaligus kesombongan sastrawan.
Cara kerja seperti itu bukan sesuatu yang mutlak. Waktu mencipta tetralogi Pulau Buru (Bumi Manusia, Anak Semua bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca), Pramoedya Ananta Toer mulai dengan mendongeng tiap malam di depan teman-teman sesama tahanan. Lalu siangnya catatan dongeng itu dia ketik. Hasil ketikan kemudian disunting dan dilengkapi data oleh Jusuf Ishak. Hal yang sama juga dilakukan oleh Agatha Christie. Dia bercerita di depan sekretarisnya yang duduk mencatat atau langsung mengetik.

Mereka berdua bisa mencipta karya sastra dengan langsung bercerita, karena sebenarnya sudah lama mempersiapkan bahan-bahannya. Sejak tahun 1950an, Pramoedya sudah membaca kisah Raden Mas Djokomono Tirto Adhi Soerjo, tokoh pers dan pergerakan nasional, yang kemudian ia jadikan tokoh tetralogi Bumi Manusia. Hingga saat bercerita di depan teman-teman setahanan di Pulau Buru, roh Tirto Adhi Soerjo itu sendirilah yang seakan hadir di sana. Detil, termasuk kelengkapan data menjadi urusan editor.
Sastra di Era Digital
Epik Gilgamesh, yang ditulis tahun 2.100 SM di Sumeria menggunakan Bahasa Akkadian dan huruf paku di atas lempengan tanah liat yang sampai sekarang masih dianggap sebagai salah satu karya sastra tertua di dunia. Teks Gilgamesh berhuruf latin, baik dalam bahasa aslinya maupun Bahasa Inggris, bisa diakses melalui situs http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c.1.8.1*#. Dunia digital sebenarnya merupakan berkah yang luarbiasa bagi mereka yang berpikiran positif.
Betapa repotnya pada zaman old, ketika kita berniat untuk mengakses karya sastra pertama dunia. Sekarang kita bisa membaca Kakawin Nagarakretagama, Pararaton, dan Babad Tanah Jawi; dengan sangat mudahnya. Mestinya, sastrawan menjadi lebih unggul dalam mempersiapkan diri untuk menghasilkan karya sastra. Sebab hampir semua data dan informasi, sekarang bisa secara harafiah disebut berada berada dalam genggaman tangan. Tapi itulah ironinya. Pada zaman serba mudah dan cepat ini, tetap tak banyak sastrawan yang rajin mengakses informasi.
Yang terjadi justru masuknya hoaks dan ujaran kebencian ke kalangan sastrawan. Diskusi, perdebatan, dan adu argumentasi; telah digantikan oleh caci-maki dan sumpah serapah melalui dunia digital, yang berujung ke ranah hukum. Dunia digital yang bisa diibaratkan gudang informasi, sekaligus pentas bagi dunia sastra, tak termanfaatkan secara optimum. Padahal di dunia digital inilah seorang sastrawan bisa mengunggah karya-karya mereka sesegera mungkin, tanpa menunggu birokrasi keredaksian sebuah media.
Tampaknya sastrawan perlu lebih rendah hati, mau belajar pada seniman tari. Selama ini tari dianggap sebagai 'kartu mati'. Tak pernah ada pentas seni tari penuh penonton. Tahun 2010, Atilah Suryajaya menggarap Matah Ati. Sejak menggagas pentas tari ini pada 2009, Atilah membuat web khusus, lalu memanfaatkan situs jejaring sosial. Selama setahun penuh latihan, ia manfaatkan dunia digital secara optimal. Hingga pentas lalu menjadi semacam kopi darat dan tiket habis terjual jauh sebelum hari H.