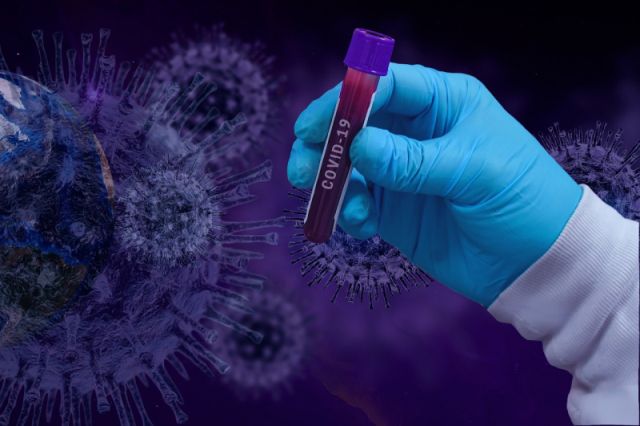Kehendak untuk hidup dalam kalut pandemi
Acap kali kita menjumpai orang yang merasa ngeri melihat satu peristiwa kebencanaan atau kecelakaan, lalu secara spontan bereaksi menutup kedua mata dengan kedua tangannya. Tetapi sesaat kemudian ia mulai merenggangkan jari-jarinya untuk mengintip kondisi korbannya.
Lebih parah lagi, dalam sebuah kecelakaan lalu lintas, misalnya, sering kita jumpai banyak orang mengerubungi korban, lalu berseru: ih ngeri!, sembari mereka melihat korban yang tergeletak sebagai objek tatapan (baca: tontonan). Mungkin salah tiga dari kita pernah mengalami dan melakukan hal serupa.
Merasa ngeri, tetapi sekaligus terus menatap korban dengan mata telanjang. Ini yang disebut menikmati kengerian. Alih-alih menghindar dari peristiwa yang mengerikan, mereka malah mendekat dan menatapnya dengan “nikmat”. Sebuah perasaan ganjil, ambivalen: ngeri tetapi sekaligus nikmat. Ngeri-ngeri nikmat.
Ambivalensi semacam ini–kurang lebih–sama dengan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tatkala membangun Tugu Peti Mati. Tugu Peti Mati sengaja ia bangun untuk mengingatkan warga tentang bahaya Covid-19 yang merenggut ribuan nyawa manusia. Alih-alih mengutuk dan menghindari kematian, Anies merayakannya dengan membangun tugu. Apakah tidak cukup terang dan nyaring patok nisan kuburan korban Covid memberikan peringatan kepada kita tentang bahaya Covid, sehingga masih harus lagi dibangun tugu?
Itu semua terjadi secara naluriah, demikian kira-kira menurut Freud. Dalam diri manusia melekat naluri ganda, yaitu thanatos atau death instinct (naluri kematian) dan eros atau life Instinct (naluri kehidupan). Thanatos ini semacam kehendak bawah sadar yang menggiring menusia pada peristiwa kehancuran dan kematian yang diwujudkan dalam bentuk tindakan: agresi, sadistik, masokis, korupsi, misalnya. Sebaliknya, eros semacam kehendak untuk melanjutkan kehidupan seperti: berkembang biak, merawat, memelihara, dan lainnya.
Melalui Tugu Peti Mati, alih-alih bermaksud mencegah kebahayaan dan kematian yang lebih besar, Anies secara tidak sadar sedang menstimulasi kebangkitan daya thanatos manusia, warga Jakarta, juga dirinya. Dengan kata lain, tugu yang berdiri kokoh itu adalah momen perayaan yang–tanpa disadari–ditopang oleh kehendak untuk mati.
Anies tidak sendirian. Apa yang dilakukannya, juga jamak dilakukan orang yang mempertontonkan peristiwa serupa melalui portal berita, media sosial, grup-grup WA dan saluran lainnya. Entah itu berupa berita jumlah kematian yang makin meningkat karena covid, video prosesi pengantaran jenazah tenaga kesehatan korban Covid, foto-foto penguburan jenazah, pasien yang “keleleran” di parkiran di sebuah rumah sakit, dan masih banyak lagi.
Kacamata dogmatis bad news is good news, tampak masih tebal dipakai pada umumnya (redaktur) media dalam meneropong dan membingkai realitas, dalam hal ini realitas pandemi.
Katakanlah semua itu dilandasi niat baik agar warga sadar pandemi dan taat protokol kesehatan. Namun, apakah semua itu membuat orang makin sadar pandemi dan taat prokes? Patut diragukan! Coba amati di beberapa kampung di Jakarta. Tidak sedikit kita jumpai anak-anak asik bermain di luar rumah, orang-orang nongkrong dan bersepeda motor tanpa menggunakan masker. Seolah status zona merah hanya sebuah warna, bukan penanda level risiko penularan.
Terlebih lagi, kalau kita amati situasi di Madura. Pada umumnya warga di sana, dengan santai mengadakan pengajian, hajatan atau aktivitas sehari-hari lainnya di luar rumah tanpa mengenakan masker. Mereka melakukan itu bersandarkan keyakinan: hidup dan mati adalah takdir yang tidak bisa dipercepat atau ditunda. Artinya dengan keyakinan itu, mereka bukan tidak menyadari bahaya dan potensi kematian akibat pandemi ini; justru sebaliknya, sangat menyadari bahwa potensi kematian selalu melekat pada dirinya sejak lahir.
Tentu kita tidak boleh begitu saja membenarkan sikap mereka itu. Bagaimanapun sikap mereka sangat berisiko dan membahayakan orang lain, terutama kelompok rentan yang memiliki daya tahan tubuh lemah.
Covid sangatlah nyata dampaknya. Derita dan kematian karena Covid benar adanya. Jelas catatan statistiknya. Sehingga semua fakta yang menyayat kalbu itu tidak boleh kita abaikan.
Akan tetapi, penyebaran berita, foto serta video horor secara masif dan intensif bukanlah pilihan tindakan yang tepat, sangat berlebihan, kontraproduktif. Penyebaran informasi negatif yang awalnya dimaksudkan menggugah kesadaran, membentuk pemahaman yang memadai, tindakan sehat dan penyelamatan diri dari Covid, justru bablas menembus hingga ke bagian terdalam manusia, membangkitkan naluri buta, naluri kematian.
Kita sesungguhnya memiliki pilihan cara bagaimana menampilkan fakta yang efeknya lebih produktif membangun pemahaman publik mengenai pandemi ini secara lebih adil, mampu membangkitkan kehendak untuk terus bertahan hidup dan menang melawan covid yang sangat “tengil” ini.
Contoh langkah sederhana: penyebaran berita positif seperti info vaksinasi, data tingkat kesembuhan, inisiatif lokal-semisal pemberian resep herbal-sebagai alternatif peningkatan imun tubuh, teknik proning sebagai swadaya mengeluarkan cairan yang menghalangi pernapasan, yoga, meditasi atau sekedar dalam bentuk seruan untuk tetap bersikap tenang, tidak panik.
Anehnya, beberapa kalangan yang mengajak untuk melihat aspek dan bersikap positif di tengah pandemi dilabeli sebagai kelompok yang sedang keracunan motivasi positif (toxic positivity), denial melihat realitas. Alhasil, narasi dan pilihan tindakan mereka tersudut, terpinggirkan oleh narasi besar ketakutan dan ilustrasi-ilustrasi horor kematian. Padahal banyak dari mereka yang memilih jalan positivitas ini berlatar profesi dokter, ahli virus dan tenaga kesehatan yang sudah banyak menyantap asam garam di lapangan.
Bisa kita bayangkan jika sikap positif dan semua bentuk positivitas lainnya disampaikan oleh orang awam? Stempel sosial seperti kadrun nyinyir Covid, antisains, herd stupidity siap ditempelkan lekat ke jidat.
Pernah saya membagikan sebuah informasi di Facebook tentang angka kesembuhan meningkat di tengah serangan Covid varian baru. Lalu seorang kawan-yang juga pengamat dan peneliti politik- menyempatkan diri menuliskan satu komentar singkat: the glass is half full. Sebuah komentar yang ambigu, entah apa maksudnya. Namun saya tetap menangkap sebentuk kebenaran dalam komentar itu.
Artinya, sebagian orang telah mengisi separuh “gelas pandemi” dengan sesak informasi dan narasi ketakutan yang menggiring orang pada kehendak untuk mati, sebagian yang lain memilih untuk mengisi data dan tindakan positif di separuh bagian ruang yang relatif kosong, longgar dan masih lega. Persis! Yang masih lega: lega bernapas. Kelegaan itu yang sangat kita butuhkan saat ini, ruang bagi life instinct, kehendak untuk hidup terus menyala, berlimpah, lalu deras mengalir, mengurai kalut pandemi.