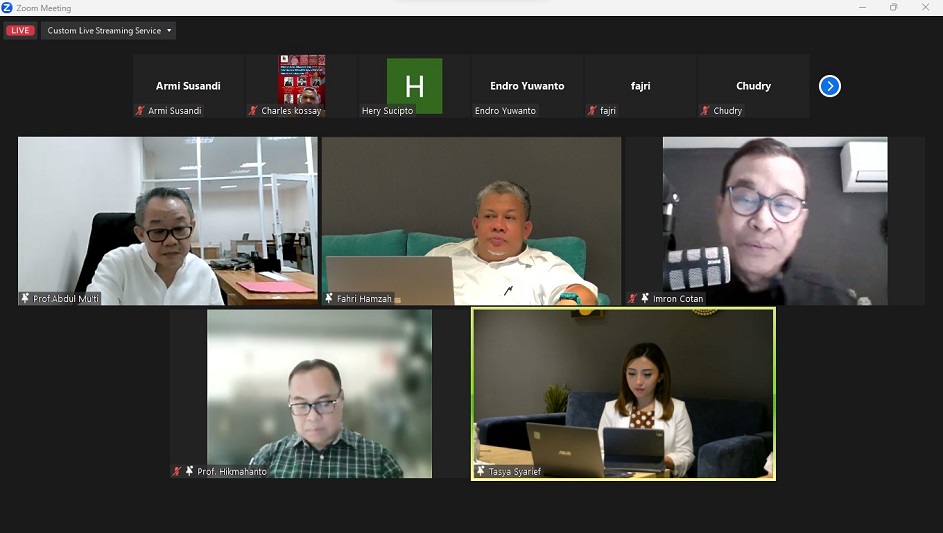Pengungkap masa lalu
Pada umumnya, manusia Indonesia modern tidak kenal lagi akan sastra lama, tak pernah membacanya, bahkan tidak pernah mendengar namanya kecuali apa yang didapatnya dari sekolah melalui pelajaran sastra lama. (Achadiati Ikram,1997)
Borobudur Writers & Cultural Festival 2019 memberi penghargaan Sang Hyang Kamahayanikan kepada Achadiati Ikram. Orang-orang mengenali sebagai tokoh berkutat di filologi. Ia memang hidup dengan naskah-naskah lama. Pembaca di "sepi" dan mengauk misteri di tulisan-tulisan jarang terbaca publik. Ia mengisahkan dan menafsirkan ke pembaca berjumlah sedikit.
Hari demi hari, menempuh jalan naskah tak membuat jemu atau patah. Achadiati Ikram malah memberi tulisan-tulisan di pelbagai majalah dan buku mengundang kita menjadi pembaca meski berpengetahuan terbatas di urusan bahasa, sastra, agama, dan sejarah.
Pada 2 Maret 1985, Achadiati Ikram memberi pidato pengukuhan guru besar di Universitas Indonesia. Ia membeberkan kepemimpinan dalam sastra Indonesia lama. Ketekunan "bersantap" naskah beragam bahasa memberi petunjukan ajaran-ajaran masa lalu tentang kepemimpinan. Achadiati Ikram mengatakan: "Ilmu kesusastraan dan foklor keduanya meneliti segi kebudayaan, dan khususnya filologi, yang merupakan bidang saya, bertugas mengkaji isi kesusastraan tertulis.
Dalam khazanah kesusastraan Indonesia lama yang begitu luas, tidak sedikit yang membayangkan atau melukiskan citra kepemimpinan yang didambakan oleh masyarakat pada zamannya." Tiga naskah dipilih di pembahasan kepemimpinan: Hikayat Pocut Muhamat, Hikayat Sri Rama, dan Serat Panji Jayakusuma.
Kita mengutip tafsiran Serat Panji Jayakusuma berkaitan tema kepemimpinan mutakhir. Tulisan masa lalu dan tafsir mungkin "suluh" mengerti situasi di Indonesia abad XXI sering ribut patokan dan identitas kepemimpinan di alur demokrasi modern. Panji Jayakusuma diceritakan menjadi pemimpin mau "bercocok tanam dan menuai padi bersama-sama rakyat." Kita lekas ingat politik-padi di masa Orde Baru dengan tokoh besar bernama Soeharto. Padi masih bukti kepemimpinan di masa sekarang.
Presiden Joko Widodo masih tetap memberi perhatian besar atas (produksi) padi dengan membuat kebijakan-kebijakan besar. Adegan memanen padi seperti Soeharto bukan lagi kewajiban di pameran makna keberpihakan ke kaum tani. Joko Widodo malah menggairahkan pertanian dengan mesin dan traktor. Semua demi capaian-capaian produksi memenuhi kebutuhan pangdan di Indonesia tetapi belum jua terpenuhi.
Adegan Joko Widodo berbeda dari Panji Jayakusuma dan Soeharto. Pada abad XX, beliau mengunjungi sawah menghasilkan adegan dan foto bertema teknologi-pertanian. Di Jawa, pemimpin selalu dimengerti sebagai "pemberi" atau mendatangkan kemakmuran. Tema penting terpikiran saat Indonesia getol memajukan pertanian dan menantikan kedatangan para investor.
Pemberian penghargaan kepada Achadiati Ikram berdekatan dengan masa "ribut" pemimpin di Indonesia. Kita memang berhak mengartikan pengabdian Achadiati Ikram membaca dan menafsirkan naskah memberi pengantar untuk mengerti masa lalu dan membekali cara baca-mengerti masa sekarang. Kepemimpinan terasa penting terbaca (lagi) di naskah-naskah lama.
Kita berganti mengingat seruan-seruan Joko Widodo saat mulai berpredikat presiden, 2014. Beliau mengawali dengan tema maritim dalam kerja dan menjalankan program-program besar selama lima tahun. Ingatan kita dikembalikan ke sejarah dan adab maritim. Pada 2019, tema itu masih berlaku tapi Joko Widodo mengimbuhi dengan keseriusan di digital dan investasi.
Kita menekuni halaman-halaman tulisan Achadiati Ikram (2017) berjudul Kemaritiman Indonesia dalam Naskah dan Laporan Lama. Kita simak kalimat apik: "Melalui jalan lautlah budaya aksara–yaitu jalan ke taraf kebudayaan yang tinggi–telah datang ke bagian dunia ini." Jalur-jalur perdagangan menentukan kedatangan pelbagai aksara dan ajaran-ajaran tersimpan di prasasti dan naskah-naskah. Pertemuan dan "pertukaran" berlangsung di rute laut.
Nusantara memiliki episode penting saat aksara melintasi lautan dan naskah-naskah penting beragam tema ditentukan oleh kultur-maritim. Achadiati Ikram menerangkan lumrah jika "kehadiran negeri-negeri Melayu tercatat dalam kesusastraan Jawa, begitu pula kehadiran budaya Jawa terekam dalam sastra Melayu." Sejarah aksara dan kesusastraan itu mula-mula bersifat maritim.
Tulisan demi tulisan mengundang pembaca memikirkan (lagi) pelbagai hal. Achadiati Ikram itu ketekunan. Peran besar tampak di Yayasan Pernaskahan Nusantara dan Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Sejak dulu, studi pernaskahan sering dikerjakan para sarjana Belanda atau Eropa. Konon, peran sarjana pribumi dimulai awal abad XX dengan kemunculan Hoesein Djajadiningrat dan Poerbatjaraka. Pada masa berbeda, jumlah sarjana kita bertambah. Sebutan bertambah jangan dipikir ada ribuan orang. Peminat studi pernaskahan di Indonesia itu minoritas.
Orang semula tak berminat tetapi lekas menekuni pernaskahan bernama Oman Fathurahman. Kesaksian Oman Fathurahman (2017) saat diajar Achadiati Ikram: "Saya beruntung karena selama menempuh pendidikan magister hingga doktoral, saya mendapat bimbingan khusus dari Prof Achadiati Ikram, mahaguru filologi yang memiliki pengetahuan luas tentang naskah-naskah Nusantara, khususnya Jawa dan Melayu. Ia adalah dosen yang sangat santun, sabar, memiliki dedikasi tinggi dalam mengajar, nyaris tidak pernah marah atau mungkin marah dengan cara yang lembut." Tekun di pernaskahan mungkin memberi pengaruh ke peneliti menjadi bijak.
Achadiati Ikram dalam buku berjudul Dinamika Pernaskahan Nusantara (2017) mengenai impian agar kaum muda mau bergumul di studi pernaskahan. Pakar terhormat itu mengingatkan: "Kita juga semua membaca di dalam sejarah perkembangan dunia pernaskahan Nusantara bahwa pada masa awal, kesarjanaan filologi hanya 'milik' para sarjana Eropa dan kemudian Australia.
Akan tetapi, belakangan kita sangat bangga bahwa sarjana-sarjana dari Nusantara sendiri telah memberikan kontribusi besar terhadap dinamika kajian di bidang ini." Abad XXI, abad cerah bagi pernaskahan. Kita mendapat publikasi penting dari para sarjana ampuh Indonesia.
Sejak puluhan tahun lalu, bacaan perkuliahan dan hasil studi memang berasal dari para sarjana besar Eropa. Kita mengenali nama penting membuat buku terbaca ribuan mahasiwa belajar sastra dan ilmu sastra. Ia bernama A Teeuw, kondang gara-gara buku berjudul Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra (1984). Ia memberi kritik: "Umumnya para filolog yang menerbitkan teks Indonesia tradisional tidak begitu sadar akan teori filologi, dan mereka biasanya masih memakai metode filologi pra-ilmiah, dengan intuisi dan pengetahuan bahasa yang sebaik mungkin; biasanya sebuah naskah dipakai sebagai legger, dasar edisi, yang kemudian seperlunya diperbaiki berdasarkan perbandingan dengan naskah lain." Buku itu "terlalu" dipentingkan di Indonesia untuk dibaca di pelbagai univeristas.
Pada masa berbeda, kita disodori buku Achadiati Ikram berjudul Filologia Nusantara (1997). Buku itu memuat tulisan-tulisan memberi gairah dan pemuliaan menggumuli naskah. Titi Pudjiastuti memberi sebutan Achadiati Ikram adalah "pemerhati, penelaah, dan pengungkap 'wajah' khazanah masa lalu" di Nusantara. Sebutan itu terbukti dengan publikasi Hikayat Sri Rama (1980) dan ketekunan mengajar agar bermunculan para sarjana di filologi. Pemberian penghargaan kepada Achdiati Ikram dalam Borobudur Writers & Cultural Festival 2019 seperti "tanda seru" bagi kita memikirkan (lagi) pernaskahan di Indonesia. Begitu.